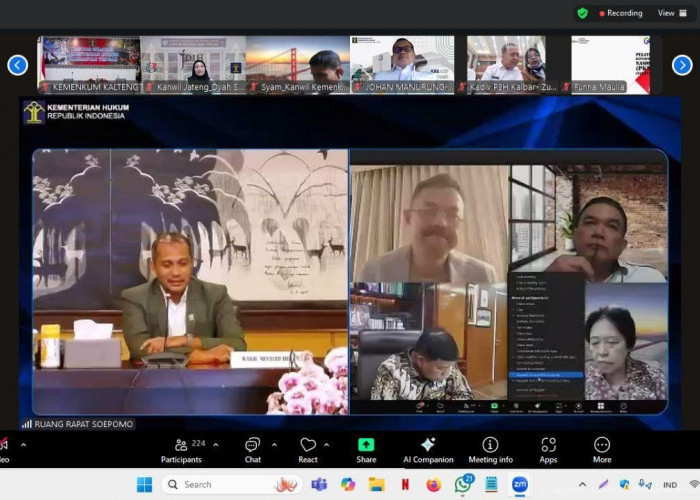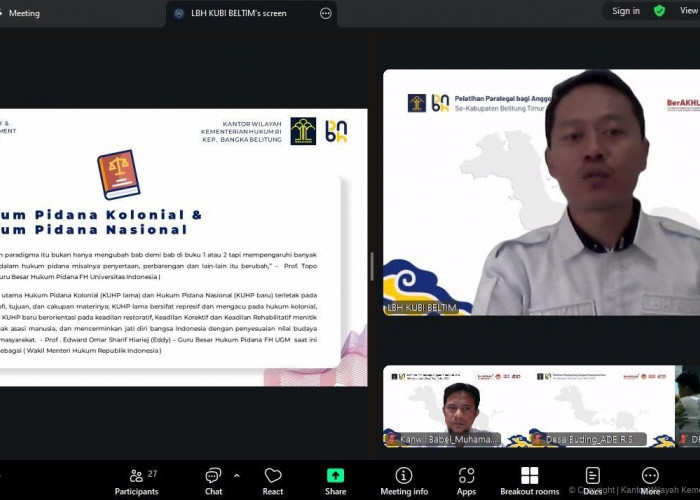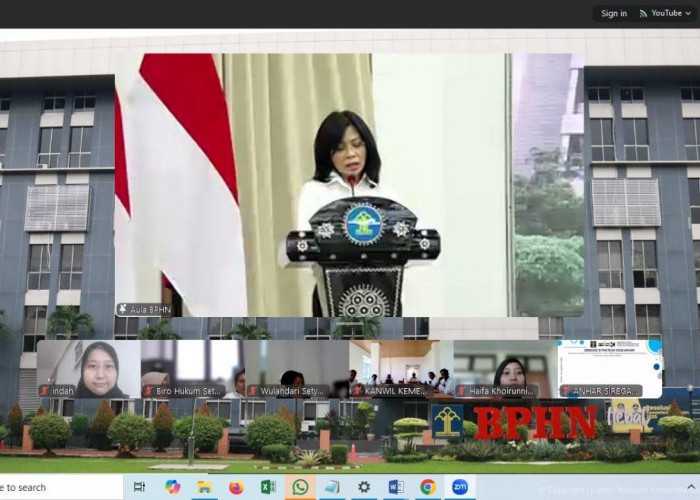Pendidikan yang Gagal Merawat: Bullying, Trauma, dan Nyawa yang Terenggut

Handika Yuda Saputra --Foto: ist
Fenomena cyberbullying turut memperumit spektrum kekerasan di kalangan peserta didik. Dengan ekosistem digital yang tanpa batas ruang dan waktu, praktik perundungan berpindah dari ruang kelas ke ruang maya dengan intensitas yang jauh lebih dahsyat. Di media sosial, identitas korban dapat dicemarkan tanpa kendali, jejak digitalnya abadi, dan trauma psikologisnya tak terhapus oleh waktu. Dalam banyak kasus, korban perundungan digital tidak hanya kehilangan rasa percaya diri, tetapi juga mengalami gangguan mental berat yang berujung pada keputusan tragis untuk mengakhiri hidup. Sayangnya, pengawasan terhadap interaksi digital peserta didik masih sangat lemah, baik oleh pihak sekolah maupun keluarga.
Pada perspektif hukum, Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah regulasi yang dapat digunakan sebagai dasar penanganan kasus perundungan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Tidak semua guru dan kepala sekolah memahami substansi regulasi tersebut, apalagi menerapkannya dalam kebijakan operasional sekolah. Penegakan hukum juga kerap lamban dan inkonsisten, sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelaku maupun institusi yang lalai.
Dengan mempertimbangkan berbagai dimensi tersebut, sudah saatnya sistem pendidikan Indonesia melakukan reorientasi secara mendasar terhadap paradigma penyelenggaraan pendidikan. Fokus pembangunan pendidikan tidak cukup berhenti pada peningkatan angka partisipasi dan capaian akademik semata, tetapi harus mencakup aspek kesejahteraan psikososial peserta didik sebagai elemen utama. Sekolah tidak boleh lagi dilihat sebagai institusi transmisi pengetahuan semata, melainkan sebagai komunitas belajar yang menjamin perlindungan, penghargaan, dan pemberdayaan semua warga sekolah tanpa kecuali.
Langkah awal yang dapat dilakukan adalah mengintegrasikan program pencegahan kekerasan dan perundungan ke dalam kurikulum pendidikan secara lintas mata pelajaran. Nilai-nilai humanisme, inklusivitas, serta penghargaan terhadap perbedaan harus menjadi semangat yang hidup dalam setiap proses pembelajaran. Guru perlu dilatih secara berkelanjutan untuk membangun sensitivitas sosial dan keterampilan identifikasi dini terhadap peserta didik yang mengalami tekanan psikologis. Di samping itu, penguatan kapasitas konselor sekolah serta pembentukan satuan tugas anti-perundungan di setiap sekolah menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda.
BACA JUGA:Menyelamatkan Muara Jelitik
BACA JUGA:Menggugat Republik: Mana Yang Layak Sejahtera, Antara Guru-Guru Honorer atau Birokrat dan Oligarki?
Transformasi pendidikan juga membutuhkan peran aktif pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam memastikan pengawasan terhadap praktik pendidikan yang bebas dari kekerasan. Pemerintah perlu mengembangkan sistem pelaporan daring yang bersifat anonim dan mudah diakses oleh siswa dan orang tua. Tindak lanjut dari laporan harus terstandar, akuntabel, dan melibatkan pendampingan psikologis, hukum, dan sosial terhadap korban. Selain itu, perlu adanya sinergi antara sekolah, Dinas Pendidikan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan lembaga penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang masuk dalam kategori berat.
Keluarga sebagai entitas sosial pertama juga memiliki tanggung jawab besar dalam membangun ketahanan mental anak. Pola pengasuhan yang terbuka, komunikatif, dan suportif merupakan modal utama bagi anak untuk memiliki keberanian mengungkapkan pengalaman traumatis yang dialaminya. Orang tua perlu mengembangkan literasi pengasuhan dan memahami bahwa kekerasan, dalam bentuk apa pun, bukanlah bagian dari proses pendewasaan. Justru sebaliknya, luka psikis yang tidak tertangani pada masa anak-anak akan berkembang menjadi trauma kronis yang berdampak pada seluruh siklus kehidupan.
Kasus kematian peserta didik akibat perundungan harus menjadi momen reflektif sekaligus titik balik dalam memandang kembali tujuan dasar pendidikan nasional. Apabila pendidikan diselenggarakan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas), maka sistem yang membiarkan kekerasan berkembang justru bertentangan secara diametral dengan mandat konstitusional tersebut. Pendidikan sejatinya adalah proses humanisasi, bukan industrialisasi angka-angka.
Mencegah terjadinya perundungan yang berujung pada kehilangan nyawa tidak bisa hanya bergantung pada instrumen hukum dan kebijakan administratif. Yang lebih mendasar adalah perubahan paradigma dalam memahami relasi antarmanusia di lingkungan pendidikan. Kita harus membangun sekolah sebagai komunitas etis, di mana martabat setiap individu dihormati, perbedaan dirayakan, dan kekerasan tidak diberi ruang untuk tumbuh. Hanya dengan cara itu, kita dapat menghentikan siklus kekerasan yang telah merenggut begitu banyak masa depan generasi muda Indonesia.
BACA JUGA:KEMUNAFIKAN DAN WAJAH GANDA DALAM POLITIK
BACA JUGA:Pulau Tujuh Bukan Sekadar Gugusan Karang, Dukung Langkah Gubernur Babel ke Mahkamah Konstitusi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: