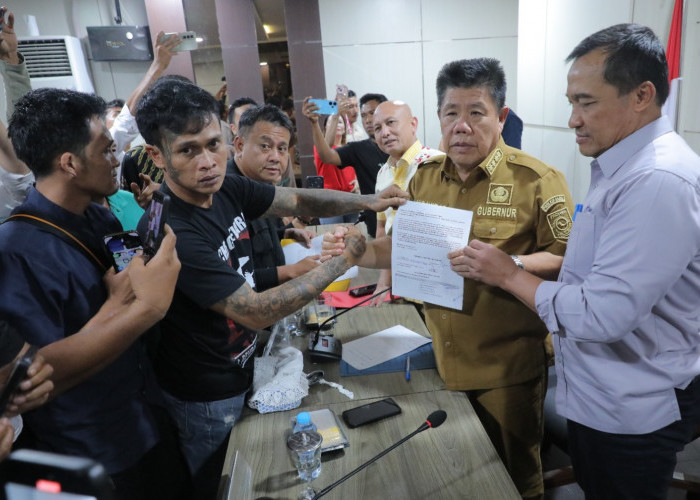Animo Hijau Masyarakat Eks Tambang Bangka Belitung: Perspektif Mahasiswa Sosiologi UBB

Ghilbar Pasesa --Foto: ist
Oleh : Ghilbar Pasesa
Mahasiswa Sosiologi Universitas Bangka Belitung
___________________________________________
Sebagai mahasiswa Sosiologi di Universitas Bangka Belitung (UBB), saya meyakini bahwa rehabilitasi lingkungan di kawasan eks-tambang timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejatinya tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial masyarakat. Melalui analisis ini, saya hendak menyoroti dua pilar sosial yang menurut kajian saya krusial: animo masyarakat dan partisipasi masyarakat. Landasan teori sosiologis mempertegas bahwa tanpa dukungan aktif dari warga lokal, justru program pemulihan lingkungan hanya akan berjalan secara parsial terbatas pada aspek teknis tanpa menyentuh aspek sosial yang mendasar. Dengan latar belakang tersebut, tulisan ini hadir sebagai refleksi sekaligus panggilan bagi semua pemangku kepentingan agar masyarakat lokal tidak sekadar menjadi objek rehabilitasi, melainkan subjek utama pada setiap tahap pelaksanaannya.
Animo Hijau Masyarakat Eks Tambang Bangka Belitung
Sebagai mahasiswa sosiologi di UBB, saya melihat bahwa keberhasilan rehabilitasi lingkungan di kawasan ekstambang timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat bergantung pada dua faktor sosial utama: animo masyarakat dan partisipasi masyarakat. Landasan teoritis yang menjelaskan kedua konsep ini mempertegas bahwa tanpa dukungan aktif masyarakat lokal, upaya pemulihan lingkungan hanya akan berjalan setengah hati.
Pertama, animo masyarakat yaitu minat, ketertarikan, dan semangat warga terhadap program lingkungan menjadi prasyarat penting. Dalam definisi sosiologis, animo mencerminkan tingkat keterlibatan sosial dan kesadaran kolektif terhadap suatu fenomena sosial. Jika animo rendah, maka partisipasi aktif akan sulit diwujudkan. Misalnya, masyarakat mungkin tidak memiliki motivasi untuk ikut menanam pohon atau menjaga vegetasi di lahan bekas tambang karena merasa “sudah bosan”, “tidak ada hubungannya”, atau “berat sendiri”. Sebaliknya, bila animo tinggi, akan muncul kemauan untuk berkontribusi, terlibat dalam gotong-royong, atau mendukung secara moral maupun praktis. Dengan demikian, menurut landasan teori, animo bukan sekedar indicator melainkan pintu masuk untuk partisipasi yang lebih bermakna.
Kedua, partisipasi masyarakat keterlibatan aktif warga dalam setiap tahap kegiatan (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi) sangat krusial. Menurut Cohen dan Uphoff (1980), partisipasi bukan hanya sekedar hadir fisik, melainkan sebuah proses sosial yang mencerminkan kesadaran kolektif dan rasa memiliki terhadap lingkungan. Dalam konteks eks-tambang timah, masyarakat yang ikut merencanakan rehabilitasi, mengawasi pelaksanaan, atau mengevaluasi hasilnya jauh lebih mungkin untuk menjaga keberlanjutan program. Sebaliknya, jika masyarakat hanya “dipakai” sebagai tenaga kerja atau “objek” tanpa rasa memiliki, maka program bisa jadi berjalan secara top-down dan kehilangan semangat lokalnya.
Ketiga, menghubungkan animo dan partisipasi dengan konteks spesifik kawasan eks-tambang timah: di Bangka Belitung, kerusakan lingkungan akibat penambangan timah (lahan rusak, sedimentasi, hilangnya vegetasi) bukan hanya persoalan teknis tetapi juga sosial. Untuk memulihkan fungsi dan daya dukung lingkungan (yang didefinisikan sebagai rehabilitasi lingkungan), diperlukan aksi bersama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat lokal. Tetapi bagaimana jika masyarakat setempat tidak memiliki animo tinggi? Maka partisipasi aktif akan sulit diwujudkan. Sebaliknya, bila masyarakat memiliki semangat dan rasa memiliki terhadap tanahnya, mereka akan lebih sigap menanam kembali, mengawasi praktik ilegal, dan menjaga hasil rehabilitasi. Maka, keberhasilan rehabilitasi lingkungan di kawasan eks-tambang timah sangat bergantung pada dua faktor sosial tersebut.
Keempat, dari pengalaman di lapangan dan hasil penelitian (contoh: Yunus, 2021; Rahmawati, 2020) menunjukkan bahwa faktor ekonomi lokal, kepemimpinan komunitas, dan struktur sosial masyarakat mempengaruhi animo dan partisipasi. Ini berarti bahwa sebagai mahasiswa sosiologi, kita tidak boleh hanya melihat angka atau laporan teknis, melainkan harus memperhatikan kondisi sosial budaya Masyarakat misalnya apakah masyarakat memiliki pekerjaan lain setelah tambang, apakah ada pelatihan atau motivasi untuk terlibat, apakah pemimpin lokal mampu mendorong warga. Tanpa penguatan faktor-faktor sosial ini, maka program rehabilitasi bisa terhenti, bahkan gagal.
Sebagai kesimpulan, saya berpendapat bahwa untuk mewujudkan rehabilitasi lingkungan yang berkelanjutan di kawasan eks-tambang timah Bangka Belitung, maka paradigma yang harus digulirkan adalah: membangkitkan animo masyarakat terlebih dahulu melalui pendidikan lingkungan, kampanye kesadaran, pemberdayaan komunitas kemudian menyediakan ruang nyata untuk partisipasi masyarakat dalam setiap tahap program. Jika kedua aspek ini diabaikan, maka program teknis yang canggih sekalipun bisa gagal karena tanpa dukungan sosial yang kuat.
Sebagai mahasiswa sosiologi di UBB, saya mengajak semua pemangku kepentingan untuk menjadikan masyarakat lokal bukan sebagai objek rehabilitasi, tetapi sebagai subjek utama dengan suara, semangat, dan peran aktif. Dengan demikian, rehabilitasi bukan hanya pemulihan fisik lingkungan, tetapi juga pemulihan sosial: membangun komunitas yang sadar, tangguh, dan peduli terhadap lingkungan mereka sendiri.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: