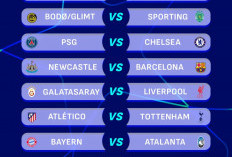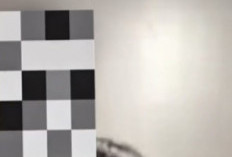Sarjana Bukan Segalanya

Ilustrasi wisuda--Foto: Ant
Sarjana penting
Pendidikan tinggi tetap memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas individu. Seorang sarjana memperoleh bekal teoritis dan metodologis yang lebih luas, mulai dari kemampuan analitis, penguasaan teknologi, hingga keterampilan komunikasi publik.
Dalam hal profesi penegak hukum misalnya, penyidik dengan latar belakang sarjana hukum lebih siap memahami asas peradilan pidana, menafsirkan pasal-pasal undang-undang, dan menyusun berkas perkara yang berstandar pengadilan. Tanpa fondasi akademik semacam ini, kesalahan prosedural dapat berakibat fatal bagi hak warga negara maupun keberlanjutan proses hukum.
Pentingnya gelar sarjana juga terlihat dalam kerja legislasi. Fungsi parlemen yang menuntut penyusunan regulasi responsif dan visioner jelas membutuhkan kapasitas intelektual tinggi. Legislator dengan bekal pendidikan formal lebih berpeluang memahami tata hukum, memetakan masalah sosial-ekonomi, serta merumuskan kebijakan berbasis bukti.
Begitu pula pada jabatan eksekutif tertinggi, seorang presiden idealnya memiliki kemampuan membaca dinamika global, menimbang kepentingan nasional, dan merancang strategi pembangunan berjangka panjang yang tidak mungkin dicapai tanpa kedalaman intelektual.
Indonesia pun membutuhkan sarjana. Kompleksitas tantangan kebangsaan hari ini menuntut sumber daya manusia dengan kapasitas analitis yang matang. Persoalan penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, transformasi digital, hingga geopolitik global tidak dapat dijawab hanya dengan keterampilan praktis. Keberadaan sarjana di ruang-ruang strategis menjadi syarat agar negara tidak tertinggal dalam persaingan internasional.
Di tingkat birokrasi, aparatur dengan latar pendidikan tinggi lebih siap menghadapi perubahan regulasi, mengelola data, dan merancang kebijakan berbasis bukti. Di sektor swasta, lulusan perguruan tinggi membawa inovasi dan jejaring global yang memperkaya daya saing ekonomi. Sementara di masyarakat sipil, sarjana berperan sebagai katalisator gagasan, penggerak advokasi, dan penopang demokrasi deliberatif.
Dengan kata lain, Indonesia tidak bisa menafikan pentingnya sarjana. Namun, yang perlu diwaspadai adalah kecenderungan menempatkan ijazah sebagai penentu tunggal kualitas manusia. Gelar akademik adalah fondasi, tetapi arah pembangunan bangsa tetap ditentukan oleh integritas personal, konsistensi kepemimpinan, dan sistem kelembagaan yang sehat.
BACA JUGA:UU dan Perpres MBG Untuk Tata Kelola Berkelanjutan
BACA JUGA:Tambahan BLT di Akhir 2025
Bukan segalanya
Realitas pendidikan di Indonesia masih menghadapi kesenjangan mendasar. Hingga kini, kebijakan nasional baru mewajibkan pendidikan dasar sembilan tahun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia baru mencapai 8,77 tahun, setara kelas IX SMP.
Bahkan, sejumlah provinsi masih berada jauh di bawah angka tersebut, seperti Papua dengan hanya 7,15 tahun, Kalimantan Barat 7,71 tahun, dan Nusa Tenggara Barat 7,74 tahun. Kondisi ini memperlihatkan bahwa akses pendidikan tinggi belum merata, bahkan masih menjadi privilese kelompok tertentu. Menjadikan gelar sarjana sebagai syarat minimal untuk jabatan publik berpotensi menciptakan eksklusivitas dan menutup kesempatan bagi warga negara lain yang secara konstitusional memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi.
Selain itu, tingginya pendidikan formal tidak otomatis sejalan dengan integritas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat pada 2021 bahwa 86 persen pelaku korupsi yang ditangani lembaga ini adalah lulusan perguruan tinggi, bahkan mayoritas bergelar magister.
Fakta ini menegaskan bahwa ijazah tinggi tidak menjadi benteng terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa budaya integritas dan sistem pengawasan yang kuat, pendidikan tinggi justru dapat menjadi modal bagi elite untuk memperluas akses rente dan memperdalam jurang ketidakadilan.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: