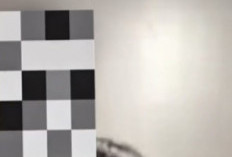Lungoi

Ahmadi Sofyan - Penulis Buku /Pemerhati Sosial Budaya--
Oleh : Ahmadi Sofyan - Penulis Buku / Pemerhati Sosial Budaya
DUA hari setelah lebaran, lempah kuning dan lempah darat adalah menu yang paling dicari masyarakat Pulau Bangka. Rendang daging, ayam dan berbagai jenis makanan lebaran yang dianggap mewah ternyata begitu mudah membuat “lungoi” alias “langok”. Ini sesungguhnya memiliki makna atau filsofi dalam kehidupan kita bahwa…
Baru sehari atau dua hari setelah lebaran, kenyataannya lidah kita orang Bangka tidak akan pernah bisa dipungkiri bahwa ingin segera kembali ke Lempah Kuning atau Lempah Darat. Rasa memang tak bisa berbohong. So, tidak seharusnya kita sombong dengan persoalan selera.
Padahal, jauh hari sebelum lebaran datang, kita sudah begitu sibuk menyusuri setiap sudut pasar untuk membeli kebutuhan, meramaikan mall dan toko untuk memanjakan mata membeli pernak-pernik rumah dan toples serta isinya guna dihadirkan untuk parade diatas meja. Tapi, kala saatnya datang, lebaran (Idul Fitri) menyapa, makanan mewah diatas meja begitu lahap kita santap hanya di pagi dan siang hari. Sorenya, kita sudah mulai terasa “Lungoi” alias “Langok” atau bosan. Ingin menyegerakan menyantap Lempah Kuning atau Lempah Darat. Sedangkan parade toples berjejer diatas meja seringkali hanya untuk dipandang yang kadangkala jarang sekali kita sentuh.
Daging sapi dan ayam yang harganya selangit, tetaplah kita beli demi menyongsong lebaran Idul Fitri. Namun ternyata makanan yang kita sebut mewah tersebut, nyatanya hanya sesaat saja kita nikmati, selanjutnya kita ingin kembali kepada kesederhanaan atau aslinya kita punya selera. Begitu juga kehidupan hiruk pikuk kota, akhirnya kita tetap ingin kembali kepada alam seperti kebun dan kesunyian. Inilah kemewahan yang sesungguhnnya, bukan tas mewah, gelang dan jam tangan mewah ala isteri pejabat.
Dari sini sesungguhnya memberikan pelajaran penting bagi kehidupan kita, bahwa apa yang kita cari, kita belikan, kita banggakan serta kita bangga-banggakan ternyata hanyalah sesaat saja. Jabatan yang diperebutkan dengan berbagai cara, harta yang didapatkan dengan menghalalkan segala cara bahkan dengan riba, kecantikan dan kemewahan yang dikejar sedemikian rupa, serta popularitas yang dijunjung tinggi untuk sebuah pencitraan, ternyata adalah semu belaka. Kehidupan yang asli, apa adanya, jauh lebih lama bertahan dan kita semua pasti akan kembali kepada keaslian walau ditutup-tutupi dengan penuh strategi. Misalnya, rumah 4 dijadikan 1 dengan kolam renang mewah. Rumah di muat di kota lain dengan 2 kolam renang plus mobil mewah dan segala macam pernak-pernik kemewahan. Pada titik akhir akan mengalami ketidaknyamanan dan ketidaktenangan, apalagi uang yang didapat dari setoran per-bulan 1 Milyar misalnya dari para bawahan. Ini cuma misalnya saja, kok.
Pointnya, jika menelisik pada “kebanggaan” kita selama ini terhadap apa yang kita miliki, sesungguhnya tidak berarti apa-apa, bahkan untuk diri kita sendiri. Apa yang kita perebutkan, kita cari dan kita beli seringkali hanya sekedar untuk menunjukkan jati diri semata, bukan untuk hal yang bermanfaat bagi orang lain (masyarakat). Kita hanya sering bangga pada sesuatu yang sebenarnya tidak memiliki harga sama sekali dimata masyarakat.
Menu Lebaran dan Ekonomi Lokal
DARI menu lebaran ini kita bisa menyaksikan berapa banyak daging dan ayam yang tidak kita produksi sendiri justru menjadi menu utama. Sehingga berapa banyak putaran uang yang di daerah kita demi memenuhi “gengsi” berlebaran. Apakah sapi dibeli dari daerah kita sendiri? Apakah berjejernya toples serta isinya itu adalah produksi tangan ibu-ibu daerah kita? Apakah ayam-ayam yang kita sikat itu adalah ayam dari kandang sendiri? Apakah baju-baju lebaran yang kita beli adalah produk lokal sendiri? Rasa-rasanya, hampir semua pertanyaan itu mendapat jawaban TIDAK.
Kadangkala saya nakal berpikir, bagaimana menu lebaran di daerah kita Pulau Bangka dan Belitung harusnya memulai dengan menu lokal, yakni Lempah Kuning dan Lempah Darat. Sedangkan daging dan ayam hanyalah sekedarnya saja. Masyarakat kita haruslah memulai memproduksi kunyit di kebun atau halaman belakang dan depan rumahnya, kue-kue yang kita saji hendaknya adalah kue-kue lokal yang dibikin oleh tangan ibu-ibu kita di daerah. Dengan ini, setidaknya ada nilai ekonomis bagi masyarakat dalam menyambut Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Kita harus mulai berpikir “mendapatkan” bukan “mengeluarkan”. Bukankah masyarakat Pulau Bangka adalah masyarakat yang paling sering “berpesta pora” makanan? Berapa banyak perayaan yang kita rayakan seperti ruwah kubur, maulid, kongnyan, perang ketupat, tujuh likur, muharram dan masih banyak lagi lainnya.
Tapi, betapa banyak yang saksikan para pedagang kebutuhan kita “berpesta pora” di negeri ini adalah masyarakat luar Bangka. Ini tidaklah salah, semua orang memiliki hak yang sama dan mencari mata pencaharian, tapi setidaknya apa yang bisa kita lakukan untuk di daerah kita sendiri dan meningkatkan ekonomi kita disini? Kitalah yang seharusnya menjadi Boss dan pemilik negeri ini. Namun, nyatanya, seluruh menu yang kita sajikan dengan menghabiskan banyak uang itu tidak dari daerah kita sendiri. Sehingga putaran uang yang ada bukan untuk kita, tapi untuk orang lain karena mereka lebih kreatif dan lebih maju dalam berpikir ekonomi serta memanfaakan peluang.
***
NAH, apakah lebaran kedepan kita akan masih tetap sama? Apakah perayaan-perayaan dalam bungkus kearifan lokal juga tidak berubah? Bagaimana taraf ekonomi masyarakat kita dengan perayaan tersebut? Ah, sudahlah, nggak usah banyak-banyak pertanyaannya dan tulisannya, ntar bikin “lungoi” alias “langok”, sebagaimana “langok”-nya saya melihat isteri pejabat dan pejabat itu yang norak di negeri ini dengan memamerkan tas mewah, gelang mahal dan jam tangan branded. “Lungoi” bukan?!
Salam Lungoi!
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: